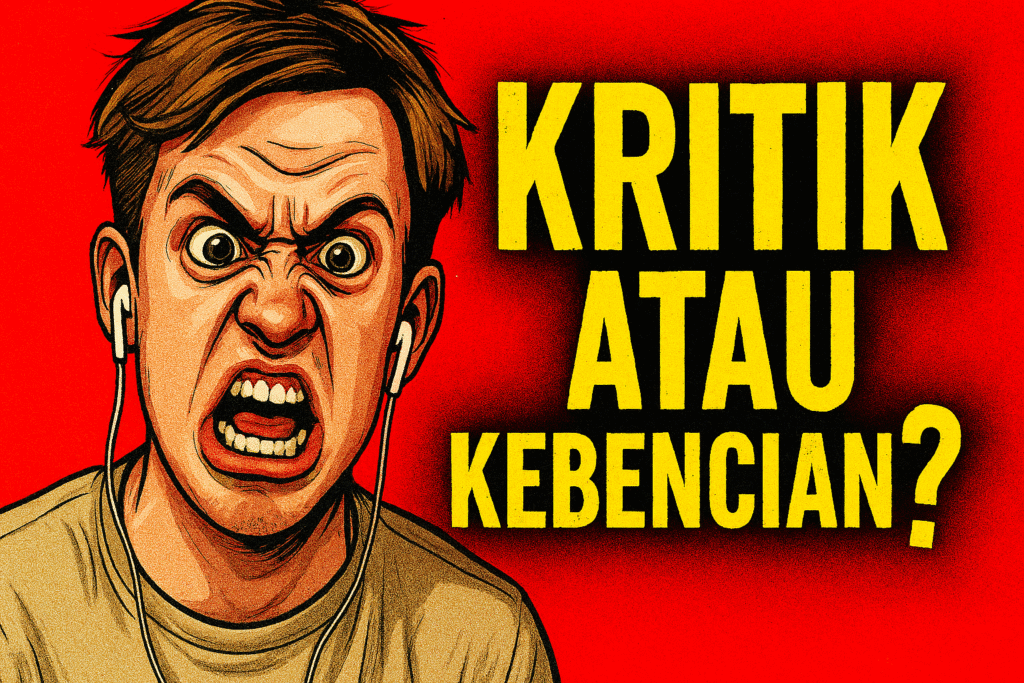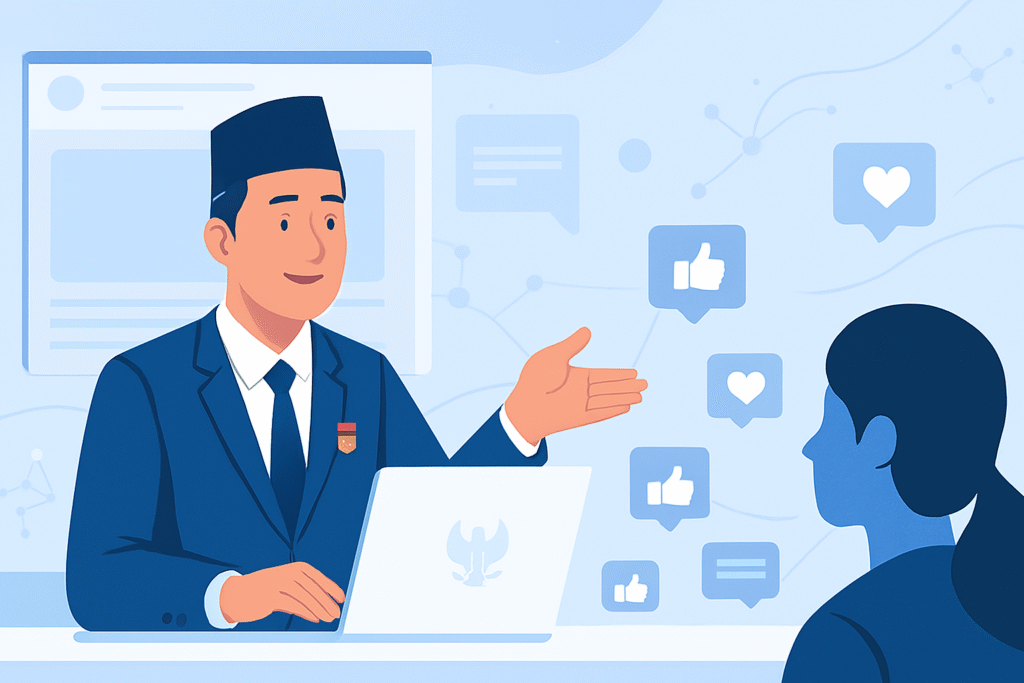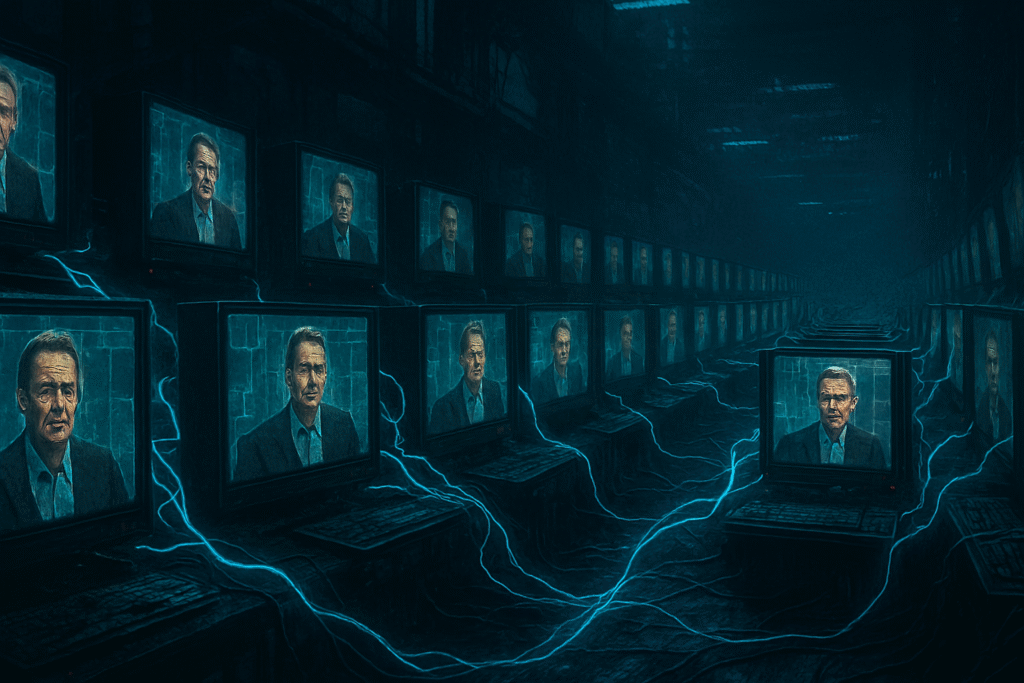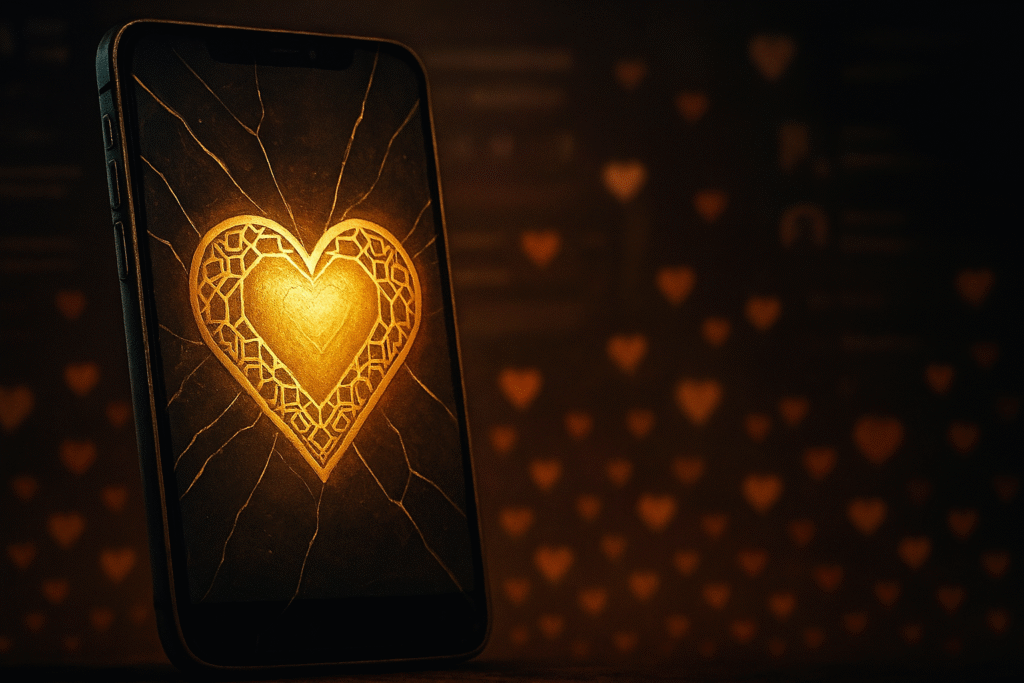Kontenpositif.com – Jagat maya Indonesia belakangan diwarnai ledakan meme dan video deepfake yang menyinggung martabat publik figur. Dari olokan visual berbasis AI hingga karikatur yang merendahkan, fenomena ini muncul di tengah kekecewaan kolektif generasi Gen Z terhadap kondisi ekonomi dan sistem pemerintahan.
Alih-alih mengkritik kebijakan secara argumen, energi frustrasi itu banyak yang dialihkan menjadi serangan personal brutal. Pertanyaannya, apakah ini masih “kritik” atau justru ekspresi emosional digital yang kehilangan akal dan etika?
Meme yang Merusak Reputasi, Batas Kritik dan Kebencian
Kritik yang sehat menyerang ide, kebijakan, dan argumen. Bukan menghujat dengan cara menyerang fisik, ras, gender, karakter pribadi. Dalam banyak kasus kontemporer, garis antara keduanya kian kabur. Misalnya, meme yang mem-deepfake wajah pejabat untuk ditertawakan, ini bukan kritik terhadap kebijakan, melainkan penghinaan terhadap martabat.
“Dalam lingkungan daring, anonimitas dan ketidaknampakan dapat memicu perilaku lepas kendali yang tidak akan seseorang tunjukkan di kehidupan nyata,” ungkap Cyberpsychology, John Suler dalam jurnal ilmiahnya The Online Disinhibition Effect. CyberPsychology & Behavior (2004).
Mengapa Kritik Berubah Menjadi Serangan Personal?
Saat perubahan sistemik terasa lamban, sebagian Gen Z merasa tak punya akses untuk perubahan langsung. Hasilnya, orang mencari pelampiasan melalui figur simbolik, yang dilihat sebagai “musuh”.
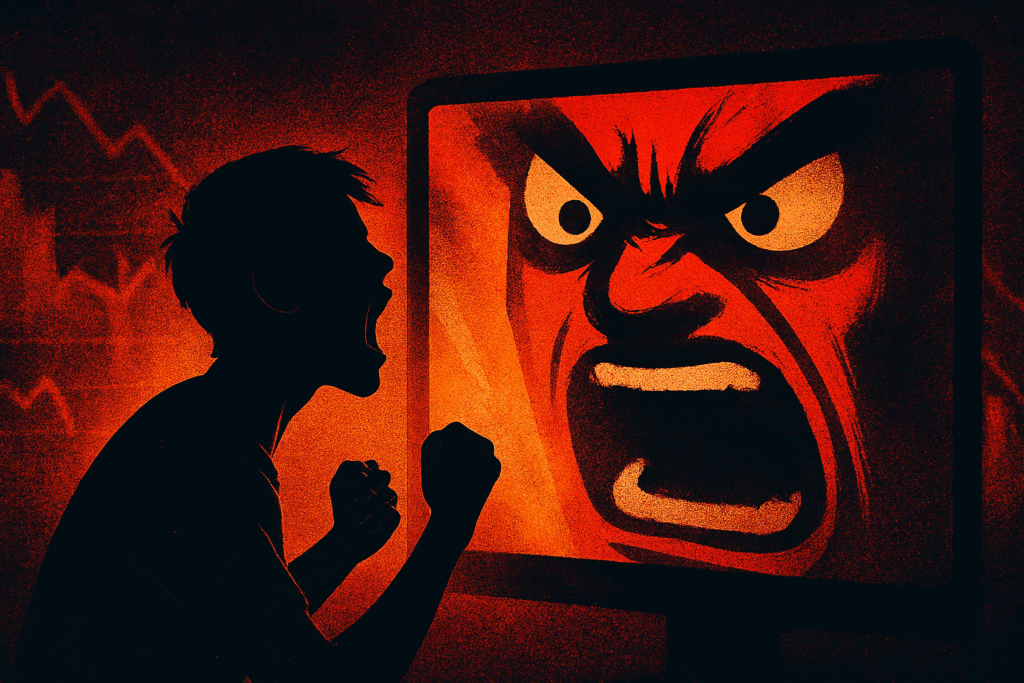
Penelitian Suler (2004) juga menyebut bahwa faktor seperti anonimitas, asinkronitas, dan minimnya kontrol otoritas membuat orang lebih “bebas” melakukan hal yang tak mereka lakukan di dunia nyata.
Hasilnya, serangan personal, trolling, meme penghinaan menjadi mekanisme coping daripada kritik konstruktif.
Ketika kritik lebih banyak untuk viral daripada berubah, maka pemuasan ego digital—“aku tahu lebih baik”—menggantikan niat system change. Kritik berhenti menjadi instrumen demokrasi, justru jadi hiburan agresi.
Ketika Teknologi Menjadi Senjata Penghinaan
Teknologi AI membuat proses penghinaan lebih cepat, murah, dan merusak reputasi. Artikel Bisnis.com mencatat bahwa “Data VIDA mencatat kenaikan kasus deepfake di Indonesia sebesar 1.550 % pada periode 2022-2023.” Kenaikan drastis ini menggarisbawahi betapa mudahnya teknologi menjadi alat fitnah.
Sementara Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemenkomdigi) menyatakan bahwa hingga saat ini pemerintah tengah menyiapkan regulasi komprehensif untuk mencegah penggunaan teknologi ini sebagai alat fitnah (Antara News, 2024).
Seperti diketahui, akun-akun yang awalnya dibuat dengan konsep satire sosial kini telah berubah menjadi mesin ujaran kebencian. Sasarannya bukan kebijakan, melainkan manusia. Ini menandakan kritik telah beralih ke domain fitnah.
Bahkan, paradox-nya lagi, belakangan ini ramai meme penghinaan membuat publik jadi lebih sibuk membahas etika dari penghinaan ketimbang kebijakan yang dikritisi, alhasil substansi korban sistemik dari kebijakan pemerintah terlupakan.
Empat Prinsip Etika Kritik Digital
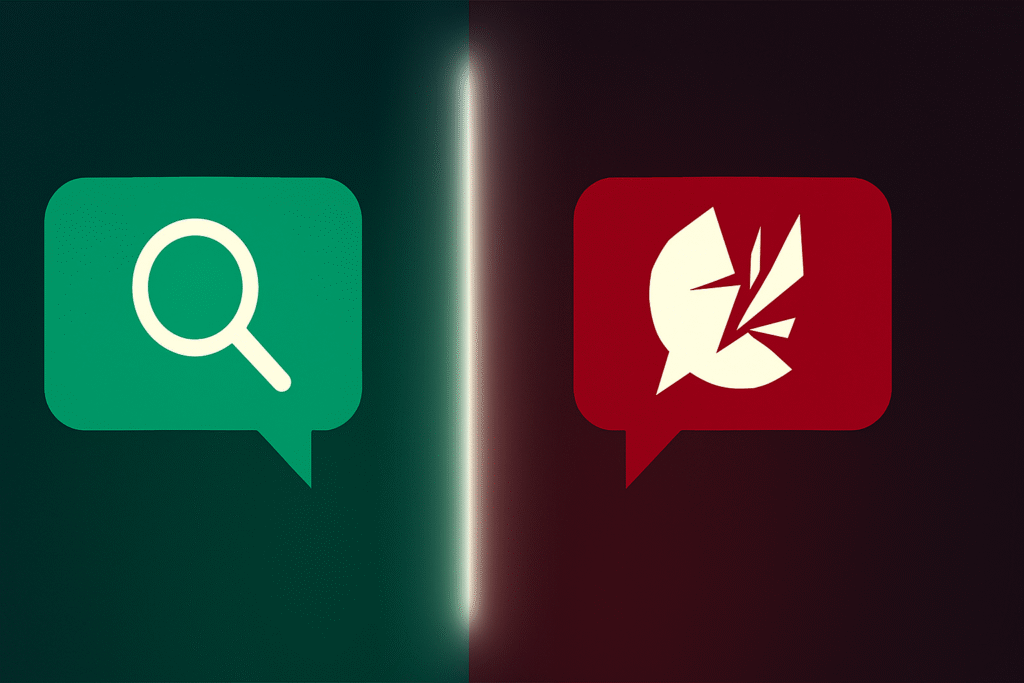
Kritik adalah hak, tetapi ia juga tanggung jawab moral. Maka dari itu, penting memperhatikan empat prinsip etika kritik digital agar lebih beradab dan berdampak. Apa saja itu? berikut ulasannya:
Pertama, mari pisahkan kebijakan dari karakter. Artinya, dalam mengkritik pemerintah serang output kebijakannya (anggaran, efektivitas program), bukan aspek personal pejabat.
Kedua, lakukan audit niat (Tawadhu’ Sosial). Sebelum membuat konten atau berkomentar menyatakan pendapat dan kritiknya, tanyakan terlebih dahulu kepada diri sendiri, apakah kritik ini untuk perbaikan? Ataukah hanya pelampiasan emosional?
Ketiga, gunakan kekuatan data, bukan dengan emosi. Sebab, kritik yang berbasis riset atau perbandingan global akan lebih efektif dan berdaya daripada meme sensasional.
Kemudian yang keempat adalah sadar jejak digital atau Digital Footprint. Pernyataan daring tak pernah hilang. Hujatan digital hari ini bisa jadi sandungan karier di kemudian hari.
Vitamin atau Racun Digital?
Kritik adalah vitamin demokrasi, tanpanya kekuasaan bisa bebas, sewenang-wenang hingga mengarah kepada otoriter. Namun saat kritik dilebur dengan kebencian dan fitnah, ia menjadi racun yang meracuni ruang publik.
Gen Z perlu kembali ke akar kritisnya yaitu data-driven, reflektif, dan beretika. Dengan demikian alangkah bijaknya sebelum tekan “post” atau “share”, tanyakan pada diri sendiri: Apakah ini kritik? Atau hujatan berkedok lelucon?
Bagikan artikel ini ke teman, komunitas, dan teman media sosial Anda. Mari jadikan ruang digital Indonesia menjadi panggung kritik beradab, bukan arena ego tanpa kontrol.