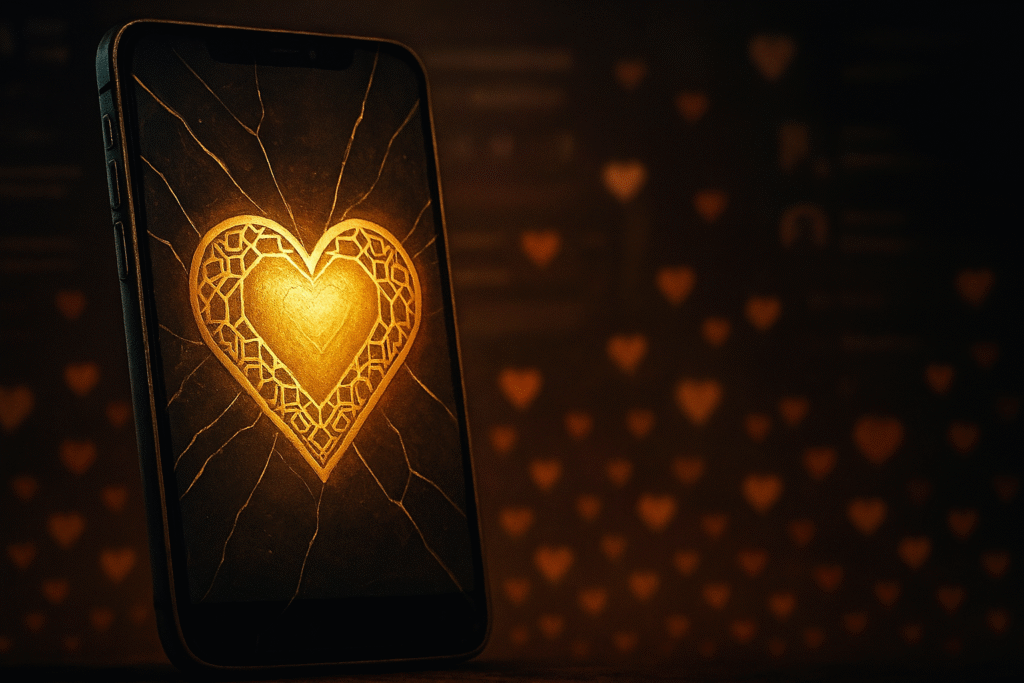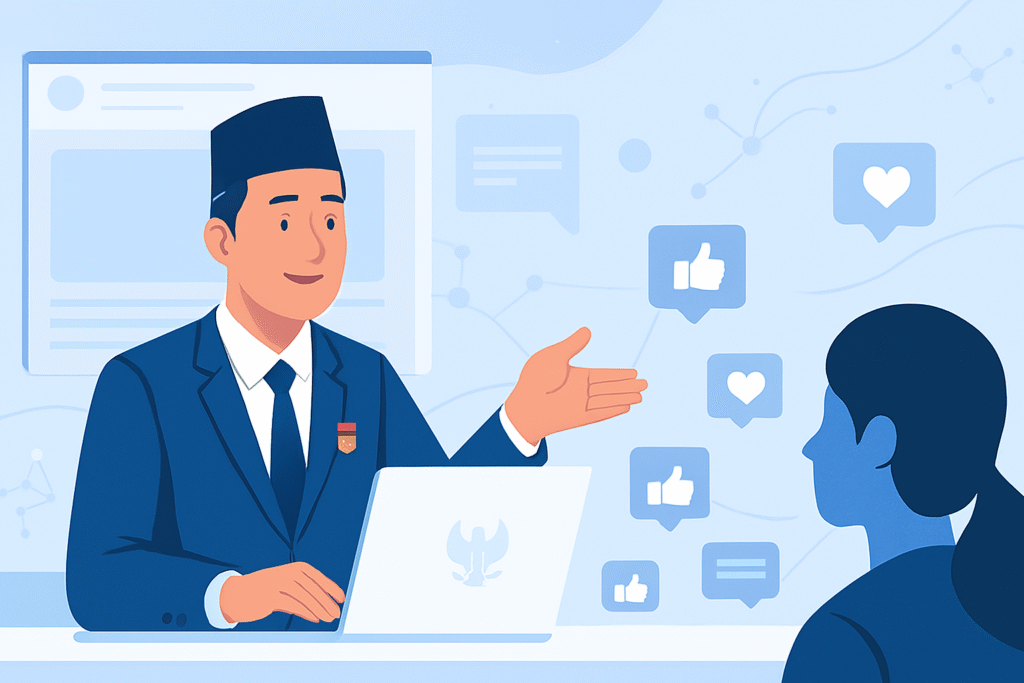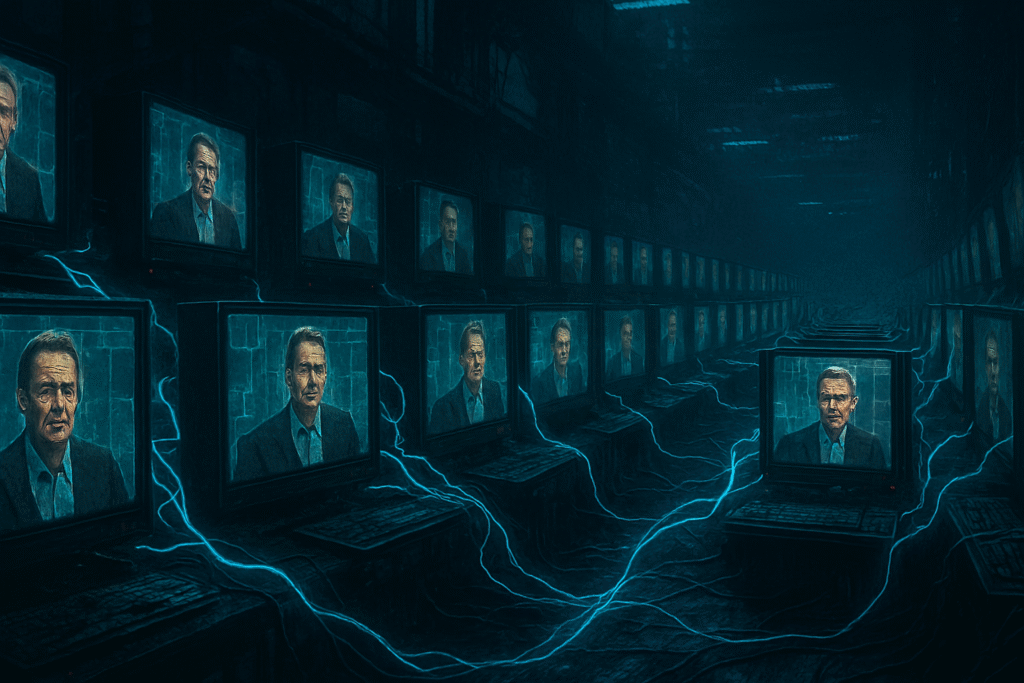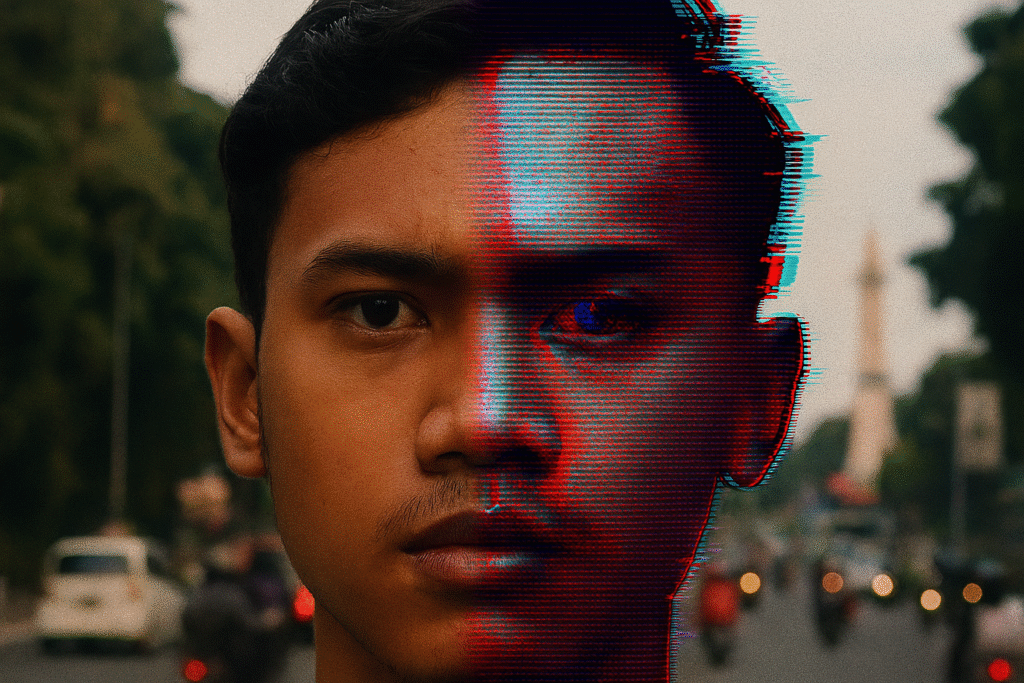Kontenpositif.com – Media sosial hari ini bukan sekadar ruang berbagi, melainkan panggung validasi. Dari story sahur, video sedekah dengan musik sendu, hingga unggahan tiket umrah atau kutipan religius di feed, semuanya bersaing untuk mendapatkan likes dan engagement.
Di satu sisi, fenomena ini menandakan meningkatnya minat masyarakat terhadap nilai-nilai spiritual. Namun di sisi lain, muncul gejala baru yang lebih halus namun berbahaya yaitu riya’ digital, ketika ibadah dan amal kebaikan dilakukan atau ditampilkan bukan semata karena Allah, melainkan karena followers.
Bagi Generasi Z yang tumbuh dalam ekosistem validasi algoritmik (validation seeking generation), batas antara berbagi inspirasi dan pamer spiritualitas menjadi sangat tipis. Lalu, di titik mana unggahan religius berubah menjadi riya’? Apakah menghapus konten tersebut menjadi bagian dari taubat digital?
Sekadar diketahui, artikel ini menelaah fenomena riya’ digital dalam perspektif teologis dan sosial, berdasarkan kajian ilmiah terbaru dari sejumlah universitas Islam di Indonesia, dan menawarkan langkah praktis “Audit Niat 360°” agar Gen Z dapat tetap ikhlas beramal di tengah godaan algoritma.
Anatomi Riya’ Digital, Ketika Ibadah Dijadikan Konten
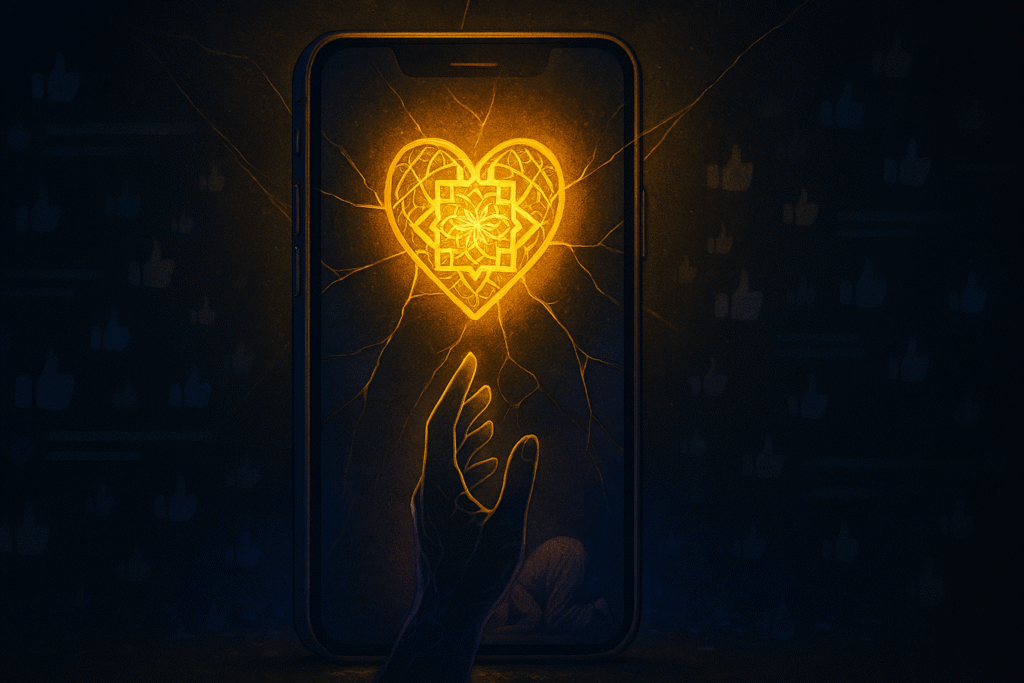
Dalam Islam, riya’ berarti melakukan amal kebaikan dengan niat agar dilihat atau dipuji manusia. Sedangkan sum’ah berarti mengabarkan amalan yang telah dilakukan agar didengar dan diakui orang lain. Keduanya dikategorikan sebagai syirik kecil karena mencampuradukkan niat ibadah kepada Allah dengan dorongan memperoleh pujian sosial.
Imam Al-Ghazali dalam Ihya’ Ulumuddin menegaskan bahwa riya’ adalah “penyakit hati paling halus”, sebab sering kali dilakukan tanpa disadari. Hati yang riya’ bukan hanya kehilangan keikhlasan, tetapi juga menjadikan amal yang sejatinya bernilai tinggi menjadi kosong dari pahala.
Kajian “Riya’ in the Realm of Social Media” (UIN Mataram, 2023) menjelaskan bahwa media sosial menjadi ruang baru bagi munculnya bentuk riya’ modern. Tiga mekanisme utamanya adalah, Amplifikasi Publik, Validation Trap, dan Ego Algorithm.
Amplifikasi Publik: Satu unggahan kebaikan yang bisa menjangkau ribuan mata dalam hitungan detik. Hal ini memperbesar potensi seseorang menyesuaikan niat ibadah dengan respons audiens, bukan dengan keridhaan Allah.
Validation Trap: Penelitian Epis: Islamic Studies Journal (IAIN Tulungagung, 2024) menemukan bahwa Gen Z urban Muslim kerap mengalami tekanan sosial untuk terlihat “saleh digital” agar diakui sebagai bagian dari komunitas yang religius. Likes dan views menjadi tolok ukur spiritualitas palsu.
Ego Algorithm: platform seperti Instagram dan TikTok mendorong pengguna menampilkan versi terbaik dirinya, termasuk dalam hal ibadah. Algoritma mendorong konten yang menarik secara emosional, bukan yang paling jujur secara spiritual.
Refleksi Ulama Klasik dan Tantangan Modern

Imam Al-Ghazali mengingatkan bahwa hati adalah benteng utama seorang mukmin. Di era digital, benteng itu kini diserang tanpa henti oleh notifikasi, komentar, dan algoritma. Riya’ digital tidak selalu muncul dari niat buruk; ia sering berawal dari niat baik yang digeser sedikit oleh dorongan untuk diakui.
Ulama kontemporer seperti Prof. Quraish Shihab (2022) dalam tafsir Al-Misbah Digital Lecture menegaskan bahwa berbagi amalan boleh, selama niatnya untuk menginspirasi, bukan memamerkan. Namun batasnya sangat halus: “Ketika hati gelisah menanti like atau komentar, maka niat itu sudah tercemar.”
Pertanyaan yang kini ramai dibahas di forum-forum dakwah digital adalah “Apakah berdosa menampilkan ibadah di media sosial?” Para ulama klasik maupun kontemporer sepakat bahwa niat adalah penentu hukum.
Sehingga dua kemungkinan besar muncul yaitu, yang pertama diperbolehkan (Jika Niatnya Dakwah dan Edukasi). Jika unggahan dimaksudkan untuk menginspirasi dan mengajak orang lain berbuat baik, maka hal itu dapat bernilai ibadah, selama hati tetap terjaga.
Sebagaimana sabda Nabi SAW dalam HR. Bukhari no. 6499, “Sesungguhnya setiap amal tergantung niatnya, dan setiap orang akan mendapatkan sesuai dengan apa yang diniatkannya.”
Misalnya, konten dakwah informatif, video kajian, atau testimoni kebaikan yang memotivasi orang lain. Banyak lembaga dakwah digital menggunakan strategi ini untuk meningkatkan kesadaran zakat, wakaf, dan kebaikan sosial.
Kemudian yang kedua malah bisa jadi tercela (Jika Niatnya Riya’ dan Sum’ah). Namun jika unggahan diniatkan untuk memperoleh pujian, simpati, atau validasi sosial, maka amalan itu menjadi riya’ yang terlarang.
Penelitian Hidayah: Jurnal Pendidikan dan Syariah (Aripafi, 2025) menyebutkan bahwa pamer ibadah digital termasuk dalam bentuk baru dari “kecenderungan riya’ sosial-teknologis”, yakni ketika manusia menggunakan teknologi untuk membangun citra kesalehan.
Lantas, bagaimana hukumnya menghapus postingan yang merupakan perwujudan dari tanda taubat digital, jika seseorang sadar bahwa unggahannya ternyata dilandasi riya’? Para ulama fiqh modern, termasuk Ustaz Ahmad Sarwat, L.C., MA. dalam Fiqh Kontemporer Online (2024) berpendapat bahwa menghapus postingan tersebut termasuk bagian dari taubat.
Alasannya, menghapus berarti menghentikan potensi dosa lanjutan dari pamer. Menunjukkan penyesalan dan kesadaran diri. Meluruskan kembali orientasi ibadah kepada Allah semata.
Namun, jika postingan itu sudah viral dan berdampak positif bagi orang lain (misalnya menginspirasi sedekah), maka yang lebih dianjurkan adalah mengklarifikasi niat, bukan semata-mata menghapus.
Audit Niat 360 Derajat, Panduan Praktis bagi Gen Z

Menjaga niat di era algoritma bukan perkara mudah. Maka dari itu, diperlukan tiga strategi spiritual praktis yang dapat menjadi filter pribadi sebelum menekan tombol post.
Pertama, The Silent Score (Melatih Niat Murni). Tentukan satu ibadah pribadi (misalnya sedekah subuh, membaca Al-Qur’an, atau shalat sunnah) yang tidak akan pernah Anda unggah di media sosial.
Ini menjadi “skor internal” Anda sekaligus sebagai bukti bahwa masih ada ruang ibadah yang murni tanpa saksi digital. Dalam psikologi spiritual, praktik ini menumbuhkan intrinsic motivation, yaitu motivasi yang lahir dari kesadaran diri, bukan dari pengakuan publik.
Kedua, Pause Ikhlas (Jeda 30 Menit Sebelum Post). Setelah melakukan amalan, berikan jeda 30 menit sebelum mengunggahnya. Jeda ini memberi ruang introspeksi. Jika setelah 30 menit dorongan untuk mengunggah sudah hilang, berarti dorongan itu berasal dari ego, bukan niat ibadah.
Konsep ini juga sejalan dengan temuan psikologi digital yang menyebut bahwa impulse posting (posting spontan tanpa refleksi) berbanding lurus dengan kadar self-presentation anxiety atau kecemasan untuk selalu tampil sempurna.
Ketiga, Audit Niat Bertahap (Tanya Diri Sendiri). Sebelum menekan tombol post, tanyakan tiga pertanyaan sederhana: apakah unggahan ini menginspirasi orang lain atau hanya memuaskan ego saya? Kemudian jika tidak ada yang like, apakah saya masih bahagia telah beramal? Apakah saya akan menyesal jika unggahan ini viral?
Jika jawaban atas pertanyaan ketiga adalah “ya”, maka lebih baik tahan diri. Kesadaran reflektif seperti ini merupakan bentuk muraqabah digital yang merupakan sebagai upaya menyadari kehadiran Allah bahkan dalam aktivitas daring.
Spiritualitas Digital, Antara Dakwah dan Pencitraan
Fenomena religious influencer yang marak di TikTok, YouTube, hingga Instagram membawa dua sisi mata uang. Di satu sisi, mereka menjadi jembatan dakwah bagi jutaan anak muda yang mungkin tak lagi aktif di majelis taklim konvensional. Namun di sisi lain, terdapat risiko komodifikasi iman, ketika spiritualitas diukur melalui engagement rate dan monetisasi konten.
Penelitian UIN Sunan Kalijaga (2024) menyebut istilah “spiritual self-branding”, yaitu upaya membangun citra religius di media sosial untuk memperoleh kepercayaan publik. Dalam konteks dakwah, hal ini tidak sepenuhnya salah; yang menjadi masalah adalah ketika niat dakwah bergeser menjadi ajang kompetisi popularitas.
Fenomena ini memperkuat perlunya “etika digital Islam” sebagaimana disarankan oleh Wahbah Az-Zuhaili dalam Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu, bahwa setiap aktivitas publik yang membawa simbol agama harus dijaga kemurniannya dari tazayyun (penampilan berlebihan) dan sum’ah (ingin dikenal karena amalnya).
Di dunia yang segalanya terekam, ikhlas menjadi koin paling langka. Algoritma media sosial diciptakan untuk menstimulasi ego, memancing riya’, karena riya’ melahirkan engagement. Namun, manusia tetap memiliki kendali untuk memilih.
Generasi Z sebagai generasi paling digital sekaligus paling spiritual punya peluang besar menjadi pelopor “etika digital Islami.” Dengan disiplin Silent Score, Pause Ikhlas, dan Audit Niat Bertahap, setiap individu dapat membangun benteng spiritual yang tak bisa ditembus algoritma.
Menghapus postingan yang salah niat bukan tanda kelemahan, tetapi bukti bahwa hati masih hidup dan peka terhadap keikhlasan. Ikhlas di era digital bukan sekadar menjaga amal dari sorotan manusia, tapi menjaga hati agar tidak menuhankan sorotan itu sendiri.
Seperti kata Al-Ghazali: “Barangsiapa mengenal dirinya, maka ia mengenal Tuhannya.” Dan di zaman ini, mengenal diri berarti juga mengenal niat di balik setiap unggahan.