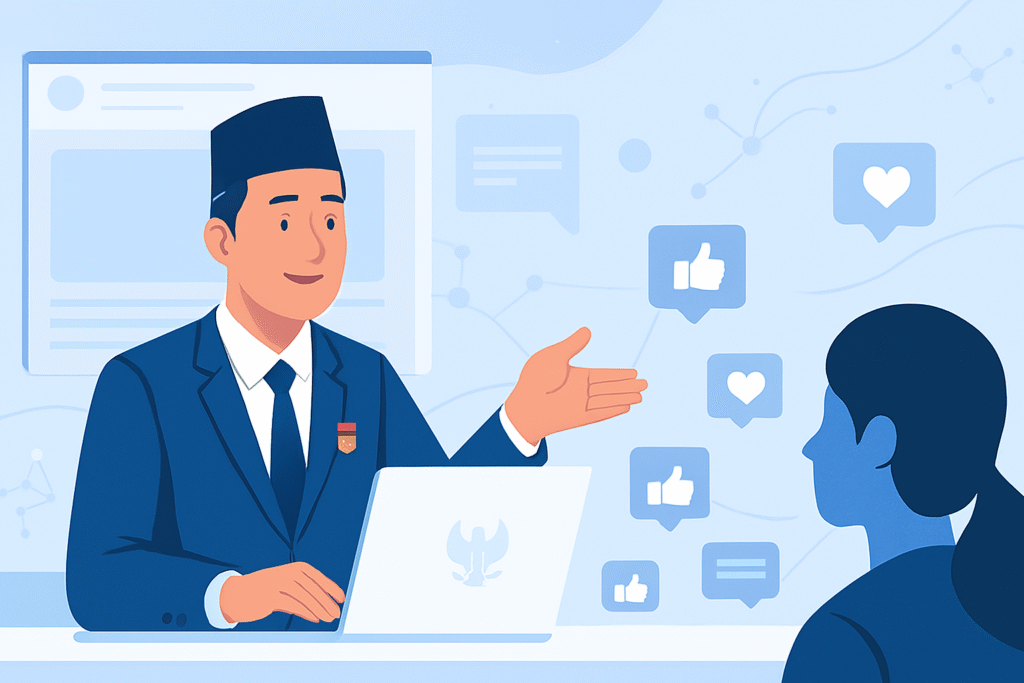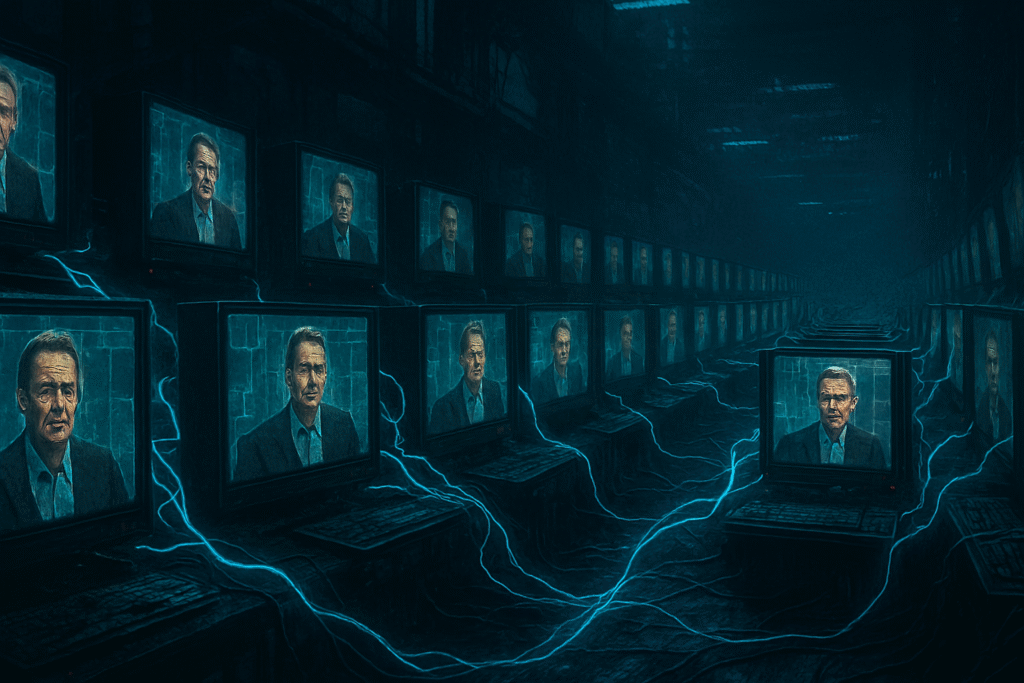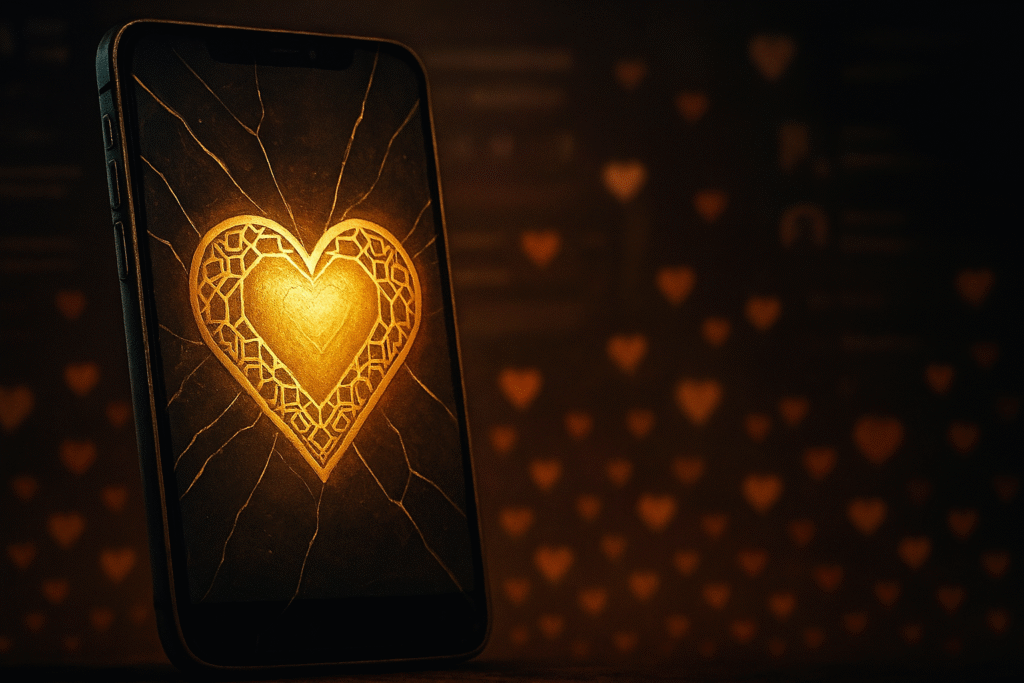Kontenpositif.com – Di dalam kabut pagi yang menyelimuti punggung Gunung Leuser, waktu seperti berhenti. Yang tersisa hanyalah desir angin yang membisikkan mantra-mantra purba dan detak jantung sendiri yang tiba-tara terasa begitu nyata. Di sebuah bivak sederhana yang berisik oleh gesekan flysheet dan tenda akibat sapuan angin, Alana (24) duduk termangu. Senyum tipisnya mengering bersama embun yang menguap. Dua belas hari menjauh dari gemerlap Jakarta, ia akhirnya menemukan kata untuk kepergiannya, “Aku pengen ngilang aja.”
Ucapan itu, yang meluncur pelan di antara helaan napasnya yang beruap, adalah sebuah pengakuan. Sebuah penyerahan diri dari generasi yang hidupnya terhubung 24/7, namun justru kehilangan koneksi paling vital, dengan dirinya sendiri. Leuser, dengan trek 12 hari dan grade kesulitan 5-nya, bukan sekadar tujuan pendakian. Ia adalah sebuah “strategic retreat”, sebuah pengasingan diri yang disengaja untuk menyelamatkan jiwa yang terkapar oleh burnout.
Mereka datang, para peziarah modern ini, ke dalam laboratorium alam seluas lebih dari 1 juta hektar ini, sebuah Cagar Biosfer United Nations Educational, Scientific, and Cultural Organization (UNESCO) yang menjadi benteng terakhir bagi orangutan, harimau, dan gajah Sumatera. Di sini, di atas tanah yang sama, dua narasi transformasi yang saling bertaut akan ditorehkan.
Senandung Lelah dari Kota di Bawa ke Leuser

Suasana kehangatan di dinginnya Camp Area Bivak Kaleng. Foto/Haryudikontenpositif.com/
Malam di Bivak Kaleng, (salah satu camp area di Gunung Leuser) menusuk tulang. Dingin yang pekat memaksa tubuh untuk merapat, sementara api unggun menjadi altar tempat mereka berbagi cerita. Alana bukanlah fenomena tunggal. Di sinilah jiwa-jiwa lelah urban itu berkumpul, membentuk sebuah kolektif yang terluka.
Habibie (29) asal Padang Sidempuan memandang bara api. Suaranya rendah namun penuh keyakinan. “Aku selama ini kerja dari umur sembilan belas… pulang itu terus. Jadi pengen ngerasain hal baru, kayak ada burnout,” ujarnya, matanya berkaca-kaca menatap nyala api yang menari-nari. Rutinitas yang menghampakan telah membawanya ke sini, mencari sebuah reset.
Di seberangnya, Wandri (27) asal Padang justru menyelipkan canda di sela-sela kelelahannya. “Soalnya (pekerjaan) membuat capek juga kan, pikiran badan,” katanya sambil tersenyum, mencairkan kesunyian malam. Namun, di balik tawanya, tersimpan beban yang sama yaitu kelelahan eksistensial.
Baca Juga: 5 Pelajaran Leuser, Resep Jurnalis Hentikan Overthinking Mental
Lalu, ada Adhitya (18), si bungsu dari Aceh Tenggara. Dengan rokok yang terjepit di jari-jari dinginnya, ia memberikan refleksi yang jauh melampaui usianya. “Biar bisa kerja biar nyaman. Enggak ada lagi yang dikejar,” ujarnya, hidungnya kemerahan diterpa angin malam. Baginya, pendakian ini adalah sebuah pelarian filosofis. “Mereka mencari… tempat yang sunyi dan akhirnya lari ke gunung… untuk mencari makna yang sempat hilang dengan kesibukan di kota.”
Mereka adalah cermin dari sebuah generasi. Dan Leuser, dengan segala keperkasaannya, menjadi cermin yang lebih besar lagi, sebuah kawasan yang menurut data Balai Besar Taman Nasional Gunung Leuser (BBTNGL) 2023 masih berjuang melawan ancaman deforestasi di zona penyangganya, meski upaya patroli SMART (Alat Pemantauan dan Pelaporan Spasial) berhasil memusnahkan ribuan jerat satwa liar setiap tahun.
Bahasa yang Hilang dalam Sunyi Leuser
Perjalanan 12 hari itu adalah sebuah proses panjang menjadi sunyi. Hari-hari awal diwarnai keheningan yang canggung, seolah setiap orang membawa temboknya masing-masing.
Namun, Habibie si introvert mulai menemukan keajaibannya di depan api unggun. “Karena kita cerita-cerita di depan api unggun, udah tidur bareng… jadi ngerasa udah dekat,” kenangnya, wajahnya yang biasanya murung kini mencair oleh kehangatan persahabatan. Di situlah “sunyi” mulai mengungkapkan wajahnya yang beraneka rupa.
Bagi Alana, sunyi adalah keheningan tanpa tuntutan. Bagi Habibie, ia adalah ruang bermain bagi jiwa yang kesepian. Sementara bagi Adhitya, ia adalah sahabat untuk berdialog dengan hati nurani.
Lambat laun, ikatan emosional pun terbentuk, disirami oleh keringat dan kepercayaan. Yazid, pendaki experienced asal Padang, sejak awal punya visi yang jelas. “Yang kedua, dapat keluarga baru. Kalau bisa kita pulang dari sini semuanya jadi keluarga selamanya.” Visinya itu, pelan-pelan, menjadi kenyataan. Keinginan untuk “ngilang” berubah menjadi sebuah kerinduan untuk terhubung secara otentik.
Di balik semua proses batin ini, hutan hujan tropis TNGL dengan curah hujan mencapai 3000-4500 mm/tahun itu tetap setia menjalankan tugasnya sebagai penopang kehidupan, menyimpan karbon dan mengatur tata air Sumatera.
Simbiosis yang Memulihkan

Mr. Nasir tengah memasak di Camp Area Lapangan Bola, Gunung Leuser. Foto/Haryudikontenpositif.com/
Namun, kisah ajaib Leuser bukan hanya tentang para pendaki. Ada sebuah transformasi timbal balik yang lebih dalam sedang terjadi.
Mr. Nasir, seorang guide senior dengan wajah yang diukir oleh matahari dan pengalaman, duduk di atas batu sambil menerawang. “Dulu kan tanaman orang sini ada ganja, ada kopi,” ujarnya, suaranya beresonansi dengan kebijaksanaan lokal. “Sekarang… yang nanam ganja pun sudah berhenti gara-gara pendaki banyak.”
Kalimat itu menggambarkan sebuah revolusi sosio-ekologis yang nyata. Kedatangan anak-anak muda yang “burnout” dari kota telah menjadi katalis bagi perubahan. Masyarakat beralih ke kopi dan jasa pemanduan. “Dampak manfaatnya terasa langsung,” ucap Mr. Nasir, matanya berbinar penuh harap.
Anwar, guide yang lebih muda, mengamini dengan semangat yang menggebu. “Asyiknya kalau di Leuser itu mendapatkan kawan-kawan baru di luar sana. Itu tuh yang bikin kami semangat.” Sebuah simbiosis mutualisme yang sempurna terjalin, para pendaki membawa pulang ketenangan, sementara warga mendapatkan napas kehidupan yang baru.
Sebuah studi lembaga konservasi 2024 memperkirakan bahwa 20% pendapatan masyarakat desa penyangga TNGL kini bersumber dari ekowisata, yang tumbuh 15% per tahun. Dukungan Amdi Izhar dari Dinas Pariwisata (Dispar) Gayo Lues pun tepat sasaran yaitu pemberdayaan. Ini adalah mozaik dari sebuah konservasi kolaboratif yang melibatkan BBTNGL, Pemerintah Daerah (Pemda), Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), dan masyarakat.
Saksikan mini-dokumenter perjalanan ini di YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=2K4J4WKGSkk&t=84s
Pelajaran Tentang Hidup dan Harimau

Mr. Nasir menunjukkan kotoran kering Harimau Sumatera yang sempat memangsa kambing hutan. Foto/Haryudikontenpositif.com/
Pada akhirnya, Leuser mengajarkan satu pelajaran universal yakni seni hidup berdampingan. Tidak hanya dengan sang penguasa rimba, harimau Sumatera, yang populasinya tersisa kurang dari 600 individu di alam liar, tetapi juga dengan “keliaran” dalam diri sendiri, semisal ketakutan, kecemasan, dan ketidakpastian.
Para pendaki belajar menerima ketidaknyamanan, persis seperti masyarakat menerima bahwa kadang sang harimau harus turun ke pemukiman. “Harapan saya… agar manusia bisa tetap hidup berdampingan… dengan harimau… tidak saling mengganggu,” harap Mr. Nasir, merangkum sebuah filosofi hidup yang dalam.
Konflik dengan satwa liar memang masih terjadi, namun frekuensinya relatif rendah berkat kearifan lokal dan sistem mitigasi yang dibangun bersama. Ini adalah sebuah metafora yang indah yakni belajar berdampingan dengan alam luar adalah refleksi dari belajar berdamai dengan alam dalam.
Ketenangan yang Dibawanya Pulang

Para pendaki menyeberangi Sungai Alas untuk kembali pulang. Foto/Haryudikontenpositif.com/
Dua belas hari bukanlah waktu yang cukup untuk menyelesaikan segala masalah kehidupan. Tapi di Leuser, waktu diukur dengan dentang jantung, bukan dengan putaran jarum jam.
Alana pun pulang. Bukan dengan jawaban, tapi dengan sebuah keheningan yang baru. Sebuah ketenangan yang tidak lagi kosong, tetapi terisi penuh oleh gumam sungai, desau angin, dan tawa baru dari “keluarga” yang ditemuinya.
Mereka semua akan kembali ke rutinitas masing-masing. Tapi seperti harapan Habibie, mereka akan “lebih bisa membuka diri.” Mereka telah menjadi bagian dari sebuah ekosistem penyembuhan yang unik, di mana generasi yang burnout dan penjaga hutan yang bertransformasi, dengan cara mereka sendiri, saling menjadi obat bagi luka masing-masing.
Dan di sanalah keajaiban Leuser yang sebenarnya berada. Ia bukan sekadar gunung, melainkan sebuah proses pemulihan yang tak pernah usai, bagi manusia maupun alamnya.(*)