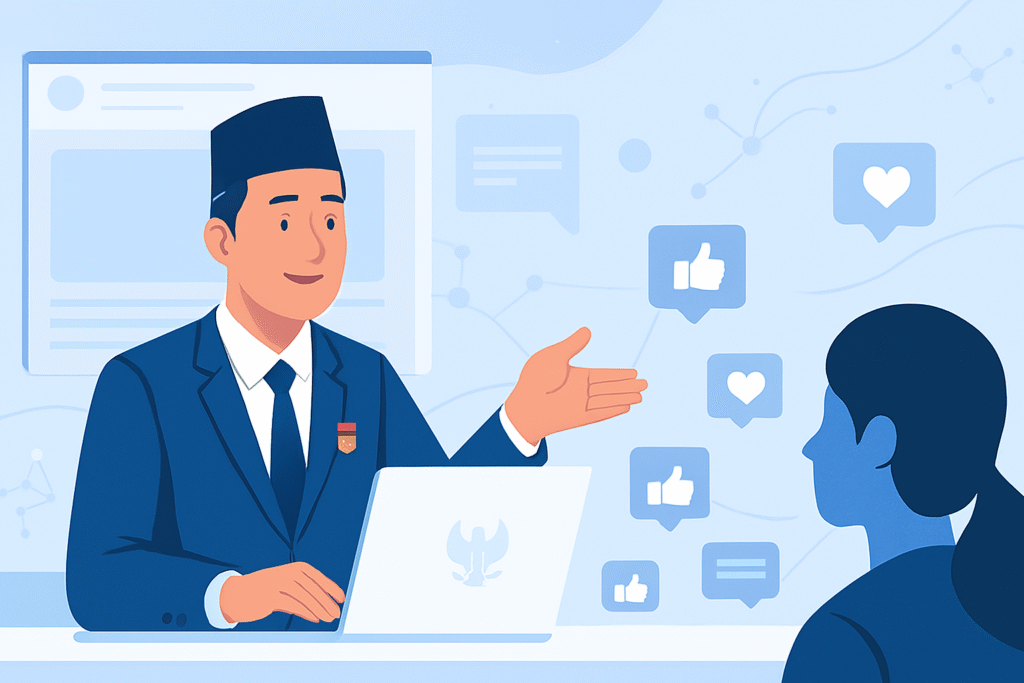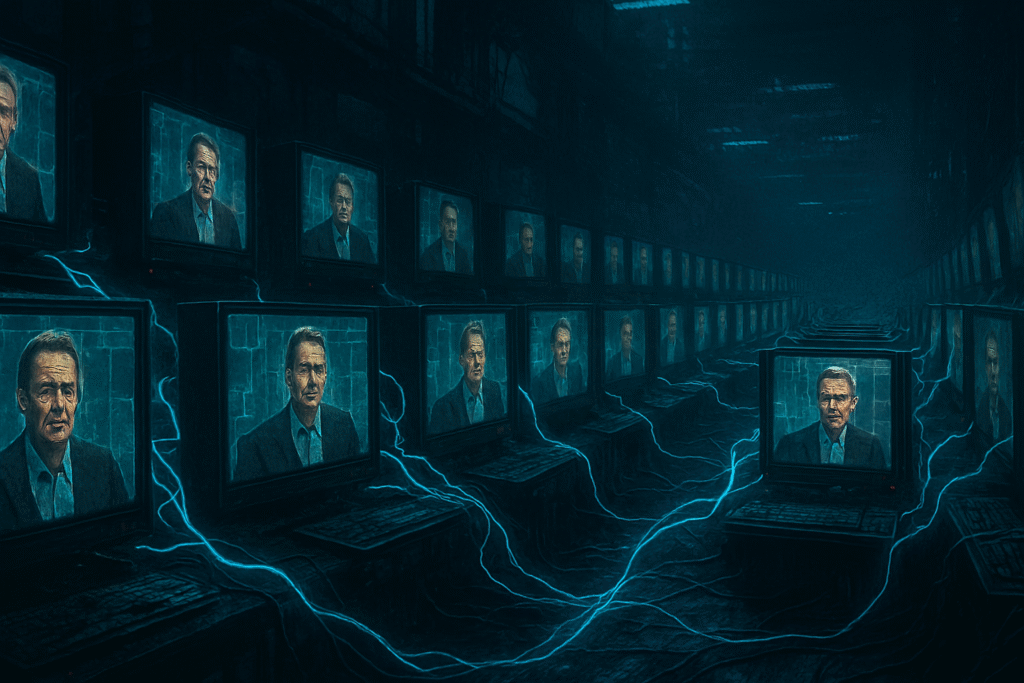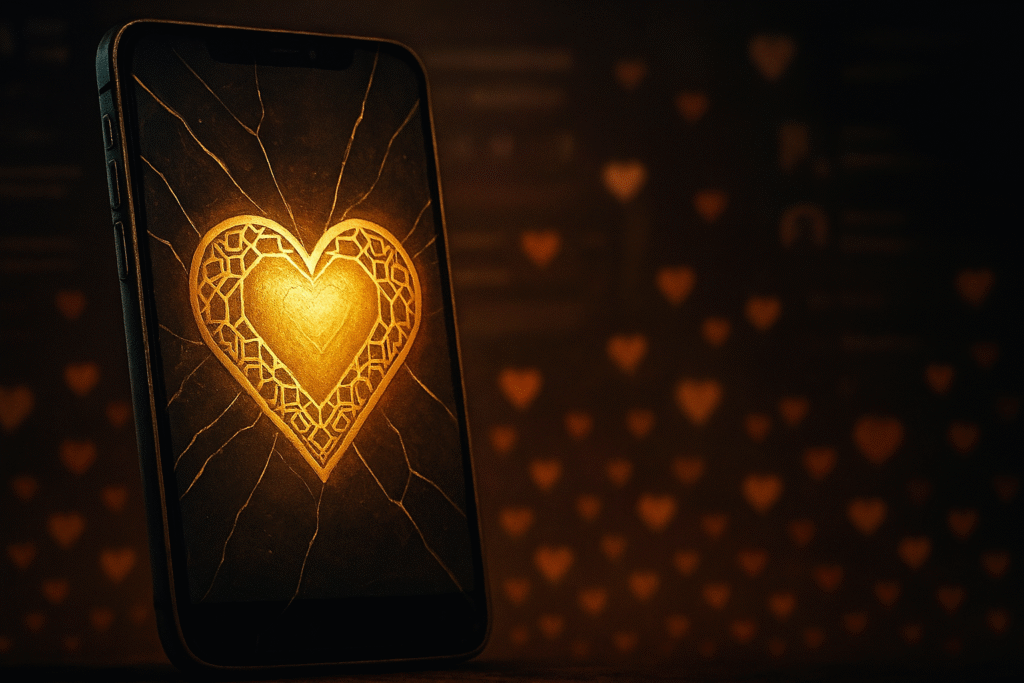Kontenpositif.com – Di abad ke-21, pertempuran terbesar tak lagi terletak di garis demarkasi fisik. Kini, pertempuran sesungguhnya terjadi di medan yang jauh lebih rapuh yaitu pikiran kita sendiri. Di tengah krisis kepercayaan yang semakin parah, terutama di kalangan generasi muda yang rentan burnout, ancaman deepfake dan misinformasi muncul sebagai senjata psikologis paling mematikan. Deepfake bukan sekadar kebohongan biasa; ia menantang hakikat keberadaan kita (Ontologi), membuat kita meragukan apa yang kita lihat dan percayai.

Beberapa waktu lalu, saya kembali dari sebuah strategic retreat di Gunung Leuser, hutan yang menjadi laboratorium resiliensi alami. Di sana, saya latihan menjaga ketenangan dan kewaspadaan untuk menghadapi ancaman harimau serta mengajarkan satu hal yaitu ketenangan dan kewaspadaan yang sama persis kita butuhkan untuk menghadapi deepfake yang bersembunyi di balik layar gawai.
Sebagai individu dan negara, kita berada di persimpangan, apakah kita akan menyerah pada kecemasan, ataukah menyusun sebuah doktrin pertahanan diri yang kokoh? Saya mengajak Anda menyelami tiga strategi utama yang mengintegrasikan kearifan masa lalu dengan tantangan masa kini. Strategi-strategi ini adalah disiplin yang harus dilatih oleh setiap orang yang ingin menjaga kewarasan.
Baca Juga: Gen Z Burnout Vs Hutan Leuser: Simbiosis Ajaib yang Memulihkan Jiwa
Ancaman Deepfake di Balik Kabut Epistemologi
Teknologi deepfake telah berubah dari alat hiburan menjadi senjata kognitif yang menggerogoti fondasi Epistemologi, ilmu tentang bagaimana kita mengetahui sesuatu. Ironisnya, saat teknologi berkembang pesat, kita justru terpaksa merangkak balik ke titik nol, mempertanyakan ulang keabsahan mata dan pikiran kita sendiri.
Konsep “Kabut Perang” (Fog of War) dari ahli strategi Prusia, Carl von Clausewitz, kini mengambil bentuk yang subtil di dunia digital. Deepfake adalah kabut tersebut. Ia menyerang realitas hingga kita tak lagi mampu membedakan.
Kasus manipulasi wajah Presiden Prabowo Subianto dan Menteri Keuangan Sri Mulyani yang tersebar di TikTok dan Facebook pada awal 2025 adalah contoh nyata. Video-video tersebut menjanjikan bantuan fiktif, menjerat lebih dari 100 korban dengan kerugian puluhan juta rupiah. Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia (Kemkomdigi) menegaskan bahwa tren ini adalah gelombang baru ancaman siber yang meluas. Prediksi Palo Alto Networks bahkan menyebut deepfake akan menjadi senjata utama dalam konflik digital global.
Bahayanya bukan hanya kerugian materi, melainkan juga krisis kepercayaan sosial dan kesehatan mental. Survei Katadata Insight Center (2024) menunjukkan 65% generasi Z dan milenial kesulitan membedakan antara informasi benar dan hoaks. Laporan Asosiasi Psikiatri Indonesia mengindikasikan bahwa satu dari tiga remaja perkotaan mengalami gangguan kecemasan yang dipicu overload informasi. Deepfake menjadi bagian dari cognitive warfare yang menargetkan persepsi dan psikologi massa. Lantas, doktrin tiga strategi pertahanan diri apa saja yang dimaksud? berikut ini ulasannya:
1. Membangun Operasi Intelijen Kognitif
Strategi pertama adalah membentuk mekanisme intelijen kognitif yang ketat di dalam diri. Sun Tzu pernah berkata, “Kenali musuhmu dan kenali dirimu sendiri, maka seratus pertempuran seratus kali menang.” Di era digital, musuh kita adalah manipulasi framing yang licik.
Analis komunikasi Erving Goffman menyatakan bahwa realitas selalu dibingkai (framed). Ketika sebuah berita terasa sangat emosional dan mendesak Anda untuk bertindak cepat, itu adalah upaya halus untuk menggeser frame pikiran Anda.
Maka dari itu, kita perlu memberlakukan protokol intelijen pribadi, di antaranya dengan cara rajin melakukan verifikasi Sumber Ganda melalui berbagai kanal. Selanjutnya, pahami nilai dan motif (Aksiologi) di balik informasi tersebut, dan selalu tanyakan, “Siapa yang diuntungkan dari kebohongan ini?”
2. Menciptakan Zona Gencatan Senjata Mental
Otak kita bukan mesin tanpa batas. Dalam strategi militer, Liddell Hart menekankan pendekatan tidak langsung dan menjaga kekuatan mental pasukan agar tidak mengalami combat fatigue. Serupa halnya, di dunia digital, kita sering menjadi korban kelelahan kognitif akibat gempuran informasi tanpa henti.
American Psychological Association (2022) mengungkapkan bahwa generasi Z adalah kelompok yang paling rentan terhadap information fatigue dan burnout digital.
Solusinya adalah menciptakan zona gencatan senjata mental yaitu waktu bebas gadget yang sakral dan rutin. Contohnya, satu jam setelah bangun dan satu jam sebelum tidur. Ini adalah bentuk logistik mental yang vital untuk memulihkan fokus dan menjaga identitas kita agar tidak terkikis oleh kebisingan luar.
Selain itu, membersihkan feed media sosial dari akun toksik adalah bentuk pertahanan aktif. Mengalihkan energi saat overload ke aktivitas fisik (grounding) juga krusial. Seperti riset American Psychological Association (2023) menunjukkan, detoks digital singkat dapat menurunkan tingkat stres hingga 27%.
3. Memperkuat Benteng Pertahanan Ultima
Jika dua strategi sebelumnya membentuk mekanisme intelijen dan zona pemulihan, strategi ketiga adalah benteng terakhir yang menentukan ketahanan kita dengan cara penguatan mindset dan nilai-nilai pribadi.
Dalam konteks perang modern, Liddell Hart menegaskan bahwa kekuatan terkuat bukan berasal dari tembok, melainkan dari semangat dan moral pasukan. Begitu pula, nilai-nilai inti seperti kejujuran, keadilan, atau keluarga, menjadi filter kognitif kita. Jika narasi bertentangan dengan nilai inti, itu adalah “bendera merah” yang harus segera direspon dengan skeptisisme.
Kita harus menerima ketidakpastian. Kita tidak akan pernah tahu kebenaran secara utuh, tetapi kita selalu bisa mengendalikan reaksi dan tindakan kita sendiri. Bangunlah “satuan tugas kepercayaan” dalam hal ini mengajak dua atau tiga orang yang bisa menjadi sistem pertahanan kolektif Anda.
Keputusan untuk tetap tenang di tengah badai deepfake adalah bentuk patriotisme kognitif yang baru.
Patriotisme Kognitif, Menjaga Kedaulatan Pikiran
Ketangguhan mental bukanlah bakat bawaan, melainkan disiplin yang harus dilatih secara sadar. Saya merasakannya di Leuser: di tengah bahaya nyata, yang diperlukan hanyalah ketenangan. Di era di mana realitas diserang, kemampuan menjaga kewarasan menjadi bentuk resiliensi modern yang mutakhir.
Dalam perspektif yang lebih luas, menjaga pikiran tetap jernih dan tidak terjebak dalam informasi palsu adalah bentuk patriotisme kognitif. Ini adalah cara kita melindungi bukan hanya diri sendiri, tetapi juga masyarakat dan negara dari kehancuran sosial yang disebabkan oleh krisis kepercayaan.
Mari kita jadikan resiliensi mental sebagai doktrin pertahanan diri di era digital. Karena menjaga kewarasan adalah perlawanan paling nyata dan berharga yang bisa kita lakukan.(*)_