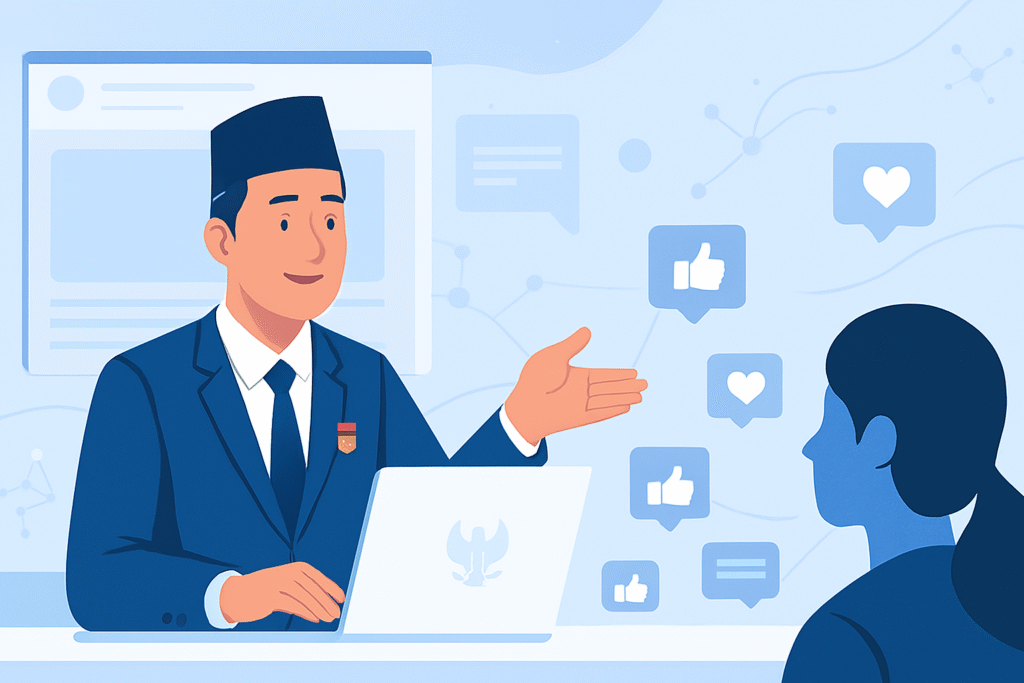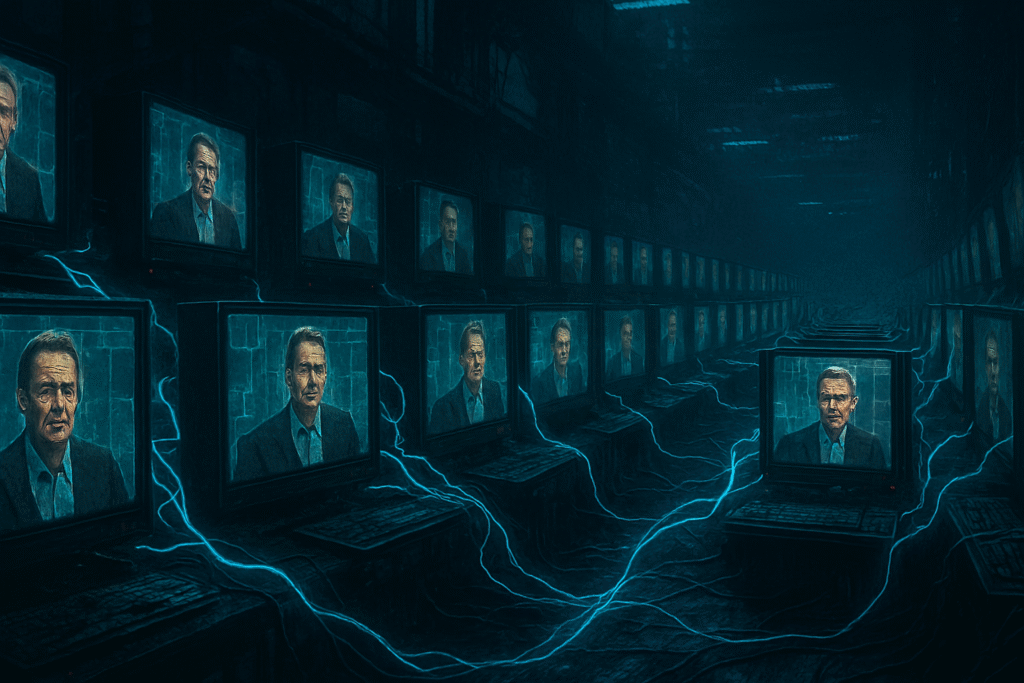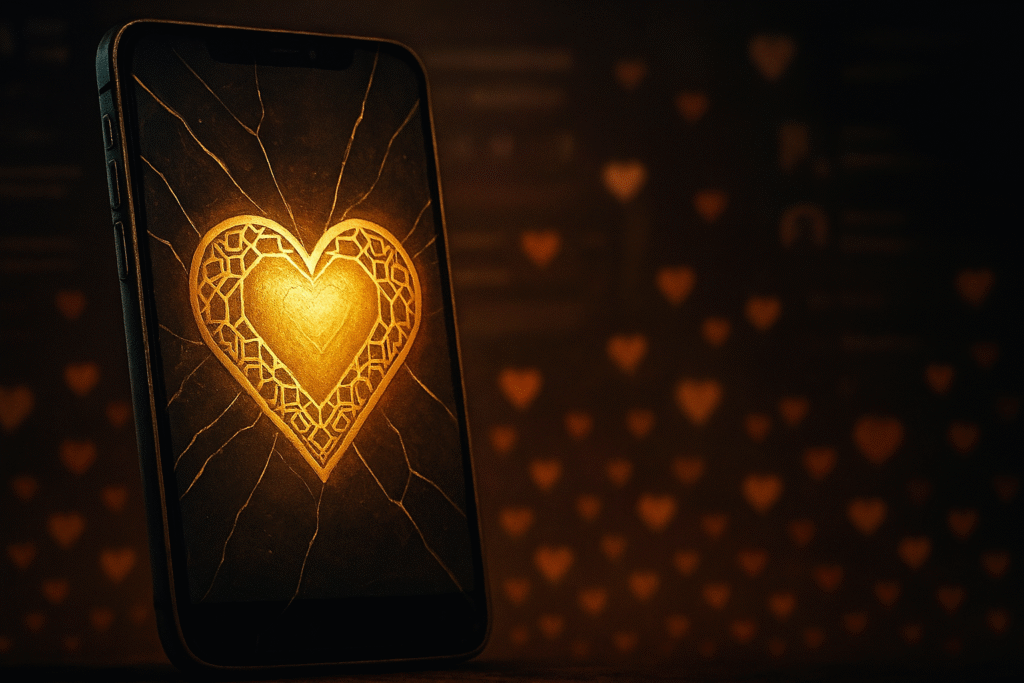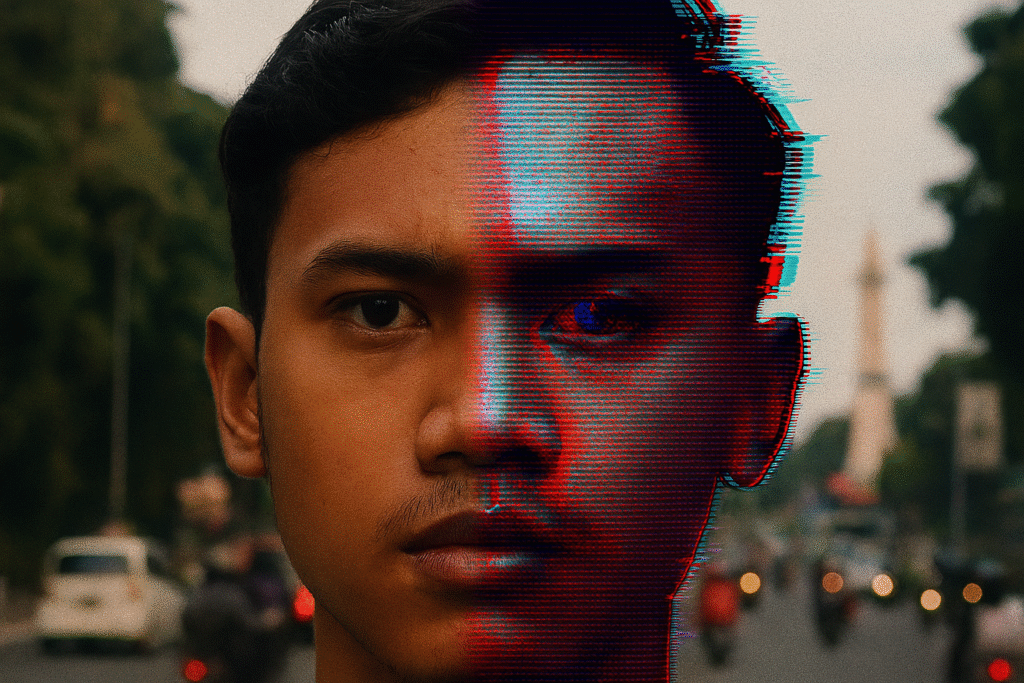Kontenpositif.com – Media sosial kini menjadi ruang utama warga untuk menyampaikan keluhan, kritik, dan tuntutan terhadap pelayanan publik. Komentar di Instagram, TikTok, Facebook, dan X (Twitter) memiliki bobot sosial dan politik yang sama pentingnya dengan forum formal seperti musrenbang atau audiensi tatap muka. Namun di tengah perubahan besar lanskap komunikasi publik ini, sebagian besar pejabat publik di Indonesia masih memperlakukan media sosial sebagai papan reklame digital.
Akun mereka dipenuhi unggahan kunjungan dinas, rapat, dan kegiatan seremoni, tetapi kolom komentar justru menjadi ruang sunyi yang penuh keluhan tak terjawab. Ketika kritik menguat, respons yang muncul bukan dialog, melainkan upaya menutup percakapan atau bahkan menggunakan buzzer untuk melawan balik warga.
Fenomena ini menandai adanya jurang komunikasi antara pemerintah dan masyarakat. Tulisan ini mengurai akar masalah komunikasi publik pejabat Indonesia, memadukan data empiris, studi kasus internasional, dan pendekatan analitis untuk merumuskan strategi komunikasi publik yang lebih dialogis, humanis, dan berbasis data.
Komunikasi Monolog dan Respons yang Pasif
Respons satu arah dari pejabat publik sebenarnya bukan hal baru dalam konteks birokrasi Indonesia. Kultur birokrasi yang hierarkis menempatkan pejabat sebagai figur otoritatif yang harus dihormati. Di banyak daerah, pejabat masih memandang dirinya sebagai pemegang kekuasaan, bukan pelayan publik yang wajib mendengar dan merespons aspirasi warga. Pola pikir ini terbawa ke media sosial, sehingga kolom komentar dianggap bukan ruang dialog, melainkan ruang yang “boleh diabaikan” atau dibatasi.
Ketakutan akan viral negatif menjadi faktor lain yang memperparah pasifnya respons. Banyak pejabat memilih diam daripada membalas komentar kritis karena takut kesalahan kecil diperbesar oleh algoritma. Platform seperti Instagram, TikTok, dan X secara default memprioritaskan konten yang memicu emosi intens—baik kemarahan maupun dukungan. Akibatnya, pejabat lebih memilih menghindari percakapan langsung daripada berisiko menciptakan bola salju viral yang berpotensi merusak reputasi politik mereka.
Literasi komunikasi digital pejabat dan tim humas yang masih rendah juga turut memperburuk masalah. Banyak akun dikelola oleh staf protokoler atau staf EO yang tidak memiliki latar belakang komunikasi digital. Mereka unggul dalam mengelola acara dan dokumentasi, tetapi tidak dilatih dalam public engagement, manajemen krisis digital, atau analisis sentimen. Media sosial akhirnya digunakan sebagai alat pencitraan, bukan sebagai kanal pelayanan publik.
Kepala Ombudsman RI Perwakilan Aceh, Dian Rubianty, dalam kuliah umum di UIN Ar-Raniry, menggambarkan fenomena ini sebagai pola “no viral, no justice”. Menurutnya, banyak pejabat hanya merespons keluhan jika sudah viral, bukan karena komitmen layanan. Riset komunikasi digital memperkuat gambaran ini: tingkat respons pejabat terhadap komentar keluhan berada di bawah 15 persen, sementara lebih dari 70 persen unggahan pejabat berisi dokumentasi kegiatan tanpa interaksi dua arah. Padahal, studi internasional menunjukkan bahwa pejabat yang aktif merespons keluhan publik dapat meningkatkan kepercayaan warga hingga 30 persen.
Dalam debat capres 2024, Ganjar Pranowo menegaskan perlunya pejabat memiliki akun media sosial untuk merespons cepat keluhan warga. Ia mencontohkan bagaimana saat menjadi Gubernur Jawa Tengah, ia mewajibkan kepala dinas memiliki akun media sosial sebagai kanal komunikasi langsung. Walaupun tidak sempurna, pendekatan ini menandai kesadaran baru bahwa responsifitas digital adalah bagian dari kinerja pelayanan publik.
Buzzer dan Erosi Kepercayaan Publik
Ketika kolom komentar menjadi ruang yang tidak nyaman bagi pejabat, sebagian memilih jalan pintas yang lebih berbahaya: penggunaan buzzer dan influencer untuk melawan kritik publik. Laporan Kompas menyebut bahwa Indonesia termasuk dalam sedikitnya 70 negara yang mengoperasikan pasukan siber untuk kepentingan politik maupun kepentingan pribadi pejabat. Buzzer ini bekerja melalui akun anonim atau semi-anonim yang memiliki jangkauan luas dan sering kali terlibat dalam penyebaran narasi yang memihak, manipulatif, atau bahkan menyerang warga yang menyampaikan kritik.
Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Sukamta, menegaskan bahwa aktivitas buzzer kini telah berubah dari tindakan individual menjadi industri yang terorganisir. Ia menambahkan bahwa banyak serangan terhadap DPR atau pejabat di media sosial bukanlah suara organik warga, melainkan hasil operasi sistematis buzzer. Ketika pejabat menggunakan buzzer untuk menghadapi kritik, pesan yang diterima publik adalah bahwa pejabat lebih tertarik menjaga citra daripada menyelesaikan masalah.
Dampaknya sangat buruk. Kepercayaan publik tergerus karena warga melihat pejabat tidak tulus dan tidak bersedia berdialog. Polarisasi digital meningkat, mengubah ruang diskusi menjadi arena permusuhan antara warga dan akun-akun anonim. Serangan balik ini bukan hanya melukai psikologis warga, tetapi juga memicu konflik horizontal di dunia digital yang dapat berujung pada kriminalisasi, doxing, atau kekerasan verbal yang berkepanjangan.
Penggunaan dana publik untuk membiayai buzzer bahkan menimbulkan persoalan etis dan hukum. Selain rentan disalahgunakan, praktik ini dapat dianggap sebagai penyalahgunaan wewenang jika dilakukan untuk kepentingan politik individual.
Studi internasional menyediakan pembanding penting. Di India, penggunaan buzzer secara masif di bawah pemerintahan Narendra Modi menciptakan ruang digital yang toksik dan penuh misinformasi. Di Filipina, pasukan siber pro-pemerintah di era Duterte digunakan untuk membungkam kritik dan membentuk opini publik melalui intimidasi digital. Namun di sisi lain, Selandia Baru di bawah kepemimpinan Jacinda Ardern menunjukkan pendekatan berbeda. Pemerintahnya mengedepankan dialog terbuka dan penjelasan yang transparan, yang berdampak langsung pada peningkatan kepercayaan publik, bahkan di saat krisis seperti pandemi COVID-19.
Studi Kasus dan Akar Masalah Komunikasi Publik di Indonesia
Jika ditinjau dari pola penggunaan media sosial, sebagian besar kepala daerah dan pejabat pusat di Indonesia menggunakan Instagram sebagai panggung personal. Foto kunjungan lapangan, dokumentasi rapat, atau kegiatan seremoni mendominasi unggahan mereka. Namun kolom komentar yang berisi keluhan, kritik, atau pertanyaan sering kali tidak mendapatkan respons. Banyak pengguna mengeluhkan bahwa komentar mereka dibiarkan tanpa balasan, sementara akun menyibukkan diri dengan unggahan pencitraan.
Di tingkat kementerian, responsivitas relatif lebih baik karena didukung tim humas yang profesional. Namun bahkan di tingkat ini, respons lebih sering diberikan pada komentar yang aman secara politik, bukan pada kritik sensitif. Pejabat sendiri jarang turun langsung merespons keluhan, sehingga percakapan publik tidak terasa autentik.
Akar masalahnya terletak pada tidak adanya standar operasional nasional untuk komunikasi digital pejabat publik. Setiap pejabat berjalan dengan gaya masing-masing, sering kali tanpa pedoman etika atau SOP responsif. Humas pemerintahan masih dipandang sebagai tim dokumentasi, bukan sebagai unit komunikasi publik berbasis data yang memiliki fungsi analitik dan engagement. Politik pencitraan didahulukan daripada pelayanan publik, sehingga komunikasi digital tidak berorientasi pada penyelesaian masalah, melainkan pada manajemen kesan.
Namun sejumlah pejabat yang menerapkan pendekatan berbeda menunjukkan hasil yang signifikan. Respons cepat, humanis, dan berorientasi solusi terbukti meningkatkan loyalitas publik, meredam konflik digital, dan memberikan dampak politik yang positif. Kasus-kasus seperti ini menunjukkan bahwa komunikasi yang efektif bukan hanya mungkin dilakukan, tetapi juga dihargai oleh publik.
Strategi Komunikasi Publik Berbasis Data dan Empati
Transformasi komunikasi publik membutuhkan fondasi yang terstruktur. Enam prinsip utama dapat membantu pejabat Indonesia membangun pendekatan komunikasi yang relevan dengan era digital dan kecerdasan buatan.
Prinsip pertama adalah respons cepat. Pejabat perlu memiliki SLA atau standar waktu khusus untuk merespons komentar kritis, idealnya dalam 24 hingga 48 jam. Dengan memanfaatkan teknologi seperti social listening otomatis dan AI analitik, proses prioritisasi keluhan publik dapat dilakukan lebih cepat dan akurat. Menteri PANRB Rini Widyantini dalam forum OECD INDIGO 2025 menekankan bahwa integrasi AI ke dalam layanan publik bukan sekadar teknologi, melainkan kehadiran aktif pemerintah dalam ruang digital modern.
Prinsip kedua adalah komunikasi humanis. Respons yang datar, template, atau formal tidak lagi relevan. Warga ingin didengar dan diperlakukan sebagai mitra dalam dialog, bukan sebagai angka statistik. Pejabat perlu memberikan penjelasan yang kontekstual, transparan, dan akuntabel.
Prinsip ketiga adalah dialog publik. Pejabat dapat mengadakan sesi Q&A mingguan, forum digital terbuka, atau sesi tanya-jawab singkat di Instagram dan TikTok. Format ini tidak hanya meningkatkan kepercayaan publik tetapi juga memperkuat kesan bahwa pejabat hadir dan siap berdiskusi.
Prinsip keempat adalah transparansi. Warga menerima jika sebuah permasalahan membutuhkan waktu penyelesaian, asalkan timeline, penanggung jawab, dan perkembangan penanganannya dijelaskan secara terbuka. Transparansi semacam ini mengurangi spekulasi dan menekan penyebaran informasi keliru.
Prinsip kelima adalah penghentian total praktik buzzer. Pejabat perlu menandatangani pedoman etika komunikasi publik yang melarang penggunaan buzzer untuk menyerang warga. Influencer dapat digunakan untuk edukasi, tetapi pembiayaan dan kontennya harus terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan.
Prinsip keenam adalah pemanfaatan AI secara etis. AI harus diarahkan untuk membantu, bukan menggantikan fungsi dialog manusia. Dengan AI, pemerintah dapat menganalisis tren keluhan, memetakan masalah per wilayah, dan mendeteksi isu yang berpotensi menjadi krisis. Artificial Intelligence Center Indonesia mencatat bahwa teknologi serupa telah digunakan untuk prediksi bencana, manajemen lalu lintas, dan penanganan keluhan publik secara real-time, menunjukkan potensi besar untuk reformasi komunikasi pemerintahan.
Hadir Secara Nyata di Era Digital
Era media sosial dan kecerdasan buatan menuntut pejabat Indonesia untuk meninggalkan pola komunikasi sepihak. Warga tidak hanya membutuhkan informasi; mereka membutuhkan dialog, empati, kehadiran, dan transparansi dari mereka yang bertanggung jawab atas pelayanan publik.
Transformasi komunikasi publik bukan hanya soal teknologi, melainkan soal mentalitas. Pejabat yang hadir secara cepat, humanis, dan dialogis akan mendapatkan kepercayaan yang lebih kuat dari warga. Sebaliknya, pejabat yang pasif, defensif, atau mengandalkan buzzer berisiko kehilangan legitimasi sosial.
Di era ketika percakapan publik terjadi dalam hitungan detik, pejabat Indonesia dihadapkan pada pilihan yang sederhana tetapi menentukan: tetap berkomunikasi secara monolog, atau berkembang menuju komunikasi publik berbasis dialog yang benar-benar menghadirkan pemerintah di tengah warganya.